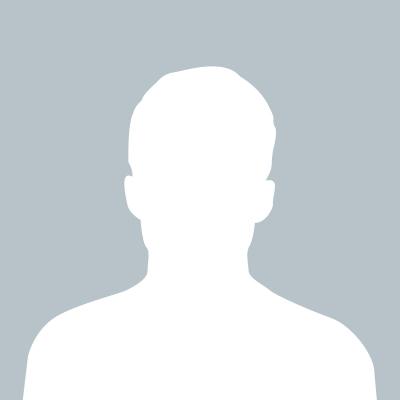Sejarah Lombok dalam Buku Kumpulan Puisi Kembali Malaut Karya Imam Safwan
Sejarah Lombok dalam Buku Kumpulan Puisi Kembali Malaut Karya Imam Safwan
Disampaikan dalam acara Bedah Buku kerja sama antara Komunitas Sastra Kamiseni (KSK) dan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Oleh Mazhar
Seorang Guru tinggal di Gondang, Lombok Utara
Imam Safwan lahir di Pemenang, Lombok Utara tanggal 12 April 1978 adalah penyair muda yang telah melahirkan banyak karya: puisi, naskah drama, dan film. Sejak kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universtas Mataram (Unram), aktif sebagai penulis, aktor, direktur artistik, dan sutradara. Beberapa buku kumpulan puisi yang lahir dari pendiri Teater NoL (North of Lombok) ini: “Gili Tiga Bidadari” (2011), “Rindu Desir Pada Pasir” (2012), Langit Seperti Cangkang Telur Bebek (2014), dan buku yang sedang dibicarakan Kembali Melaut (2019).
Bicara puisi adalah bicara tentang bentuk, bait, larik, rima, bunyi, dan makna. Ditinjau dari bentuk, puisi-puisi karya Imam Safwan (2019) mengambil bentuk puisi bebas. Puisi bebas dipopulerkan oleh Chairil Anwar dengan karya yang sangat terkenal “Aku”. Menurut Dewanto (dalam Anwar, 2016: xviii) Chairil Anwar bukanlah pelopor puisi bebas. Penyair-penyair Pujangga Baru, seperti Roestam Effendi, J.E. Tatengkeng, dan Amir Hamzah pun telah menulis puisi bebas. Puisi bebas merupakan sebuah konvensi dalam khazanah puisi modern dunia.
Walaupun bebas, bukanlah tanpa kendali. Puisi bebas memiliki disiplinnya sendiri (Dewanto dalam Anwar, 2016: xviii). Perhatikan puisi Imam Safwan (2019: 49) berikut ini.
Kembali Melaut
kami kembali setelah matahari menjangkarkan diri di gigi tengiri
merampungkan ritual saat datang fajar
asap rokok pagi itu adalah sesaji
biji biji awan yang menutup matahari
maka kami mengibas laut
di punggung gelombang yang saling berpaut.
jika kain kaca telah menyala membinarkan mata ikan di samudra
maka tiada apapun yang bisa buat kami berduka.
Meno-Trawangan, 2016
Puisi tersebut sangat memperhatikan rima, baik rima dalam maupun rima akhir. Bait pertama larik pertama terdapat rima dalam yaitu bunyi [i]. Larik kedua ada rima dalam, yaitu [a]. Larik ketiga ada rima akhir [i]. Larik keempat ada rima dalam [i], dan rima akhir [i]. Larik kelima ada rima dalam [a]. Larik keenam ada rima dalam [a] dan rima akhir [t]. Bait kedua larik pertama ada rima dalam [a], sedangkan larik kedua ada rima dalam [a], dan rima akhir [a]. Bait pertama dan kedua memiliki rima akhir a-b-a-a-c-c---d-d. Ini menunjukkan bahwa Imam Safwan (2019) sangat memperhatikan rima dalam puisinya untuk melahirkan kehindahan dan tenaga kata.
Puisi Kembali Melaut, menurut penulis memiliki kemiripan diksi dengan puisi Chairil Anwar (2016: 71) “Senja di Pelabuhan Kecil”.
Senja di Pelabuhan Kecil
Buat Sri Ajati
Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap.
1946
Perhatikan larik kelima dan keenam Kembali Melaut dengan larik ketiga dan keempat “Senja di Pelabuhan Kecil”. Kata (ber-)laut dan berpaut ada dalam kedua puisi tersebut dan sama-sama terletak di akhir larik. Apakah ini suatu kebetulan? Ataukah Imam Safwan meniru Chairil Anwar? Menurut Dewanto (dalam Anwar, 2016: xviii) Chairil Anwar selalu menjadi model atau lawan-tanding bagi penyair-penyair yang lahir kemudian. Dalam sajak-sajak Indonesia yang terbaik, kita selalu menemukan jejak-jejak Chairil Anwar.
Puisi-puisi Imam Safwan (2019) tidak mengenal sampiran. Seluruh larik adalah isi. Perhatikan Kembali Melaut. Puisi ini bercerita tentang kehidupan nelayan. Tafsir penulis terhadap puisi ini adalah para nelayan melaut ketika senja tiba. Mereka tak pernah lupa berdoa demi hasil yang melimpah. Ketika umpan telah memikat ikan, maka itu adalah kesenangan yang tiada tara. Mereka pulang setelah fajar tiba.
Bandingkan dengan “Senja di Pelabuhan Kecil”. Bait pertama dan kedua adalah sampiran, bait ketiga adalah isi. Kedua bait sampiran tersebut adalah lanskap murni, yang seakan-akan dikatakan oleh orang ketiga. Akan tetapi, sekonyong-konyong orang pertama, si aku, muncul pada bait ketiga, bukan untuk berseru, tetapi bergumam lembut, menggarisbawahi apa yang dinyatakan kalimat pertama dalam sajak itu (Dewanto dalam Anwar, 2016: xviii).
Beberapa puisi Imam Safwan (2019) ditulis dengan tipografi yang berbeda. Tipografi adalah penataan huruf, baris, dan bait secara grafis (Widarmanto, 2018: 71). Tipografi yang penulis maksud adalah penulisan larik yang menjorok ke dalam. Contohnya pada puisi-puisi: “Dusun Subagan”, “Dusun Pekatan”, “Hikayat Perahu Kayu”, “Jejak Rindu Ayah II”, “Memandikan Jenazah Kakek”, dan “Ziarah”. Keunikan tipografi ini tentu memiliki tujuan. Misalnya, pada larik kelima bait pertama, larik ketiga dan keempat bait kedua puisi “Dusun Subagan”, untuk menunjukkan adanya perpindahan (migrasi). Sementara itu, pada puisi “Dusun Pekatan” untuk menunjukkan kontradiksi pernyataan penyair antara bait pertama dengan bait kedua. Pada “Hikayat Perahu Kayu”, untuk estetika. Pada “Rindu Ayah II”, untuk menunjukkan kalimat akhir seorang ayah yang kehilangan. Pada “Memandikan Jenazah Kakek” untuk menunjukkan inti dari bait kedua puisi tersebut.
Beberapa sajak Imam Safwan (2019) menggunakan tanda petik (“...”). Ini terdapat pada: “Legenda Dusun Orong Naga Sari”, “Dusun Pekatan”, “Sireh”, “Jejak Rindu Ayah II”, dan “Ziarah”. Penggunaan tanda petik untuk menunjukkan kutipan langsung dari tokoh dalam sajak tersebut.
Imam Safwan (2019) selalu menggunakan huruf kecil di setiap awal larik maupun kata. Huruf kapital hanya dipakai pada judul puisi. Menurut analisis penulis ini adalah dalam rangka membebaskan pembaca menafsirkan maknanya. Mengutip pendapat Dewanto (dalam Anwar, 2016: xii) bahwa kata-kata memang belum selesai memancarkan keajaibannya, yaitu arti mereka yang dikandung dalam kamus barulah setahap kemungkinan arti belaka.
Puisi-puisi Imam Safwan (2019) beberapa meyisipkan diksi Bahasa Sasak, Bahasa Inggris, dan Bahasa Bima. Puisi-puisi yang menyisipkan Bahasa Sasak: “Penangkap Kelelawar”, “Daksina”, “Pedupayan”, “Menyiuang”, “Jeruman”, “Midang”, “Sireh”, “Waru Kayu Perahu”, dan “Kabar Bunga Randu”. Puisi yang menyisipkan Bahasa Inggris: “Bulan Balon Merah Marun”. Puisi yang menyisipkan Bahasa Bima: “Ke Amahami”. Penggunaan Bahasa daerah ini menimbulkan efek unik pada puisi-puisi Imam Safwan (2019), sedangkan penggunaan Bahasa Inggris dalam hal ini kata party menajamkan makna puisi “Bulan Balon Merah Marun”.
Secara garis besar puisi-puisi dalam Kembali Melaut mengangkat tema: (1) sejarah (“Dusun Subagan”, dan “Pagutan”), (2) tempat (“Legenda Dusun Orong Naga Sari”, “Dusun Pekatan”, “Telaga Wareng”, “Pada Sebuah Perkampungan”, “Batu Grantung”, “Riwayat Kali Sokong”, “Memasuki Pusuk”, dan “Ke Amahami”), (3) fenomena alam (“Fatamorgana”, “Tentang Waktu”, “Kemarau”, “Risau Kemarau”, “Hujan Yang Berlari”, dan “Imaji Negeri Awan Biri-Biri”), (4) tradisi (“Daksina”, “Pedupayan”, “Menyiuang”, “Jeruman”, “Midang”, “Sireh”, dan “Pingit”), (5) tumbuhan (“Darakanda”, dan “Perawa”), (6) ungkapan hati penyair (“Aku Ingin Mengirim Pagi”, dan “Saat di Dermaga”) (7) kehidupan pesisir (“Di Gili, Pantai Gairah, Pantai yang Dijarah”, “Bulan Balon Merah Marun”, “Pelabuhan Bangsal”, “Kembali Melaut”, “Maka Setiap Hari Kami Berkumpul di Sini”, “Arti Langit dan Bumi”, “Kabar dari Laut”, “Waru Kayu Perahu”, “Hikayat Perahu Kayu”, “Akhirnya Aku Menemukanmu”, “Di Keramba Lima”, “Pertapaan Pelampung di Lelata Kangkung”, “Kabar Bunga Randu”, “Menangkap Cumi di Bulan Purnama”, “Mimpi Nelayan Usai Hujan”, dan “Karena Angin”), (8) keluarga (“Kembali ke Rumah”, “Jejak Rindu Ayah I”, “Jejak Rindu Ayah II”, “Memandikan Jenazah Kakek”, “Ziarah”, “Kenangan pada Baju Orang Mati”), dan (9) keunikan anak manusia (“Penangkap Kelelawar”). Selanjutnya Penulis akan membahas lebih dalam puisi-puisi yang bertema Sejarah.
Kita simak puisi “Dusun Subagan” (Safwan, 2019: 1) berikut ini.
Dusun Subagan
di dusun subagan kini kami
setelah dimuntahkan gunung bali
dari subagan
dari subagan
kami pergi
pergi saat sasak masih sepi
saat anak agung mengirim api
mengirim kami
kami datang
kembali kembali pada tanah kelahiran
ke subagan
ke subagan
kami kembali
kembali menanak nasi
menanak mimpi
menanak anak
anak beranak pinak.
Kata "Subagan" dapat ditafsirkan sebagai Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dapat juga ditafsirkan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kata dimuntahkan dapat ditafsirkan sebagai diusir, atau migrasi secara paksa. Frasa "gunung Bali" dapat ditafsirkan Kerajaan dari Bali yang menyerbu Lombok tahun 1593 Masehi (Zakaria, 1988: 18--19). Frasa "anak agung" dapat ditafsirkan sebagai seorang raja yang memerintah di Lombok yang dinobatkan pada tahun 1622 Masehi dengan gelar Anak Agung Anglurah Karangasem (Zakaria, 1988: 18--19). Klausa "anak agung mengirim api" dapat ditafsirkan Raja Anak Agung dari Bali mengirim bala tantara untuk menguasai Lombok. Frasa "menanak anak" dapat ditafsirkan sebagai melahirkan keturunan dari generasi ke generasi.
Jika diparafrasakan puisi “Dusun Subagan” menjadi: di dusun (karang) subagan kini kami (berada) /setelah dimuntahkan gunung (yang ada di-) bali /dari subagan /(tepatnya) dari (kelurahan) subagan (-lah) /kami pergi/(kami) pergi saat (pulau yang didiami suku) sasak masih sepi/(kami pergi) saat anak agung mengirim api/(anak agung yang) mengirim kami.
(kini) kami datang/(kami) kembali (kami) kembali (ke-) pada tanah kelahiran (kami)/(yaitu) ke subagan /ke subagan (-lah)/ kami kembali /(kami) kembali menanak nasi/(kami kembali) menanak mimpi/(kami kembali) menanak anak/(dan) anak (kami sekarang telah) beranak pinak.
Berdasarkan tafsir kata, frasa, dan parafrasa tersebut, makna yang terkandung dalam puisi “Dusun Subagan” adalah penyair atau keluarga penyair tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun keluarga penyair tinggal di Lombok Utara, sesungguhnya nenek moyang mereka berasal dari Bali tepatnya Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Pada masa itu migrasi dilakukan dengan sistem bedol desa. Di tempat baru para imigran memberi nama pemukiman mereka sesuai dengan nama daerah asal masing-masing. Jika mereka berasal dari Karang Subagan, di tempat baru mereka menamai tempat baru itu Karang Subagan. Jika mereka berasal dari Karang Tulamben, di tempat baru dinamai Karang Tulamben dan seterusnya. Mereka migrasi karena dikirim oleh Raja Karangasem. Suatu masa penyair atau keluarga penyair berziarah ke Subagan. Di sini penulis ragu apakah penyair kembali ke Dusun Karang Subagan, Kecamatan Pemenang Lombok Utara atau ke Kelurahan Subagan, Karangasem, Bali. Keraguan ini karena di akhir puisi tidak dicantumkan lokus dan tahun penulisan.
Penulis berusaha mencari referensi sejarah Karang Subagan, tetapi tidak ketemu. Penulis hanya menemukan kata Pemenang dan frasa "Desa Bali Pemenang" dalam van der Kraan (2009). Walaupun begitu, Karang Subagan dan Desa Bali Pemenang pastilah berkaitan karena Karang Subagan merupakan pemukiman masyarakat keturunan Bali yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang.
Van der Kraan (2009: 27) menerangkan bahwa ada 800 pasukan berasal dari Pemenang yang menjadi kekuatan Ratu Agung-Agung Ngurah dalam menghadapi pemberontakan pada tahun 1891 Masehi. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1891 Masehi Pemenang yang di dalamnya termasuk Karang Subagan telah berkembang pesat hingga mampu mengirim 800 pasukan untuk berperang membela raja.
Di bagian lain van der Kraan (2009: 111) menceritakan bahwa setelah terlibat dalam perang Lombok, Jelantik bersama 1200 pasukannya bersiap-siap menyeberang ke Bali melalui pantai barat (Telok Komba) yang terletak di dekat Desa Bali Pemenang di tahun 1894 Masehi. Menurut analisis penulis Desa Bali Pemenang yang dimaksud van der Kraan adalah salah satunya Karang Subagan.
Jelaslah bahwa Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah eksis sejak tahun 1622 Masehi ketika Anak Agung Anglurah Karangasem dinobatkan menjadi raja. Karena pada tahun 1891 Masehi Pemenang mampu mengirim 800 pasukan untuk membantu Raja Mataram pada saat itu.
Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara memiliki hubungan erat dengan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali karena penduduk Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, telah bermigrasi ke Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara tahun 1622 Masehi.
Kita simak puisi kedua dalam Kumpulan “Kembali Melaut” (Safwan, 2013: 2).
Pagutan
aku telah menginjakkan kaki di tanah cerita ayah
di mana leluhurku membangun sejarah
ada titah dari raja selaparang menahan bali datang menyerang
sukamulia asal kami datang
sejak kerajaan bali didirikan kami berganti jadi pagutan.
disini aku mencari jejak para pendekar
yang berkumpul dalam padepokan
konon mereka lebih banyak mengaji pada kyai
hingga nama kebangsawanan dilepaskan
tombak dan pedang jadi hiasan
tapi api dalam hati masih tersimpan dan berkobar
barangkali karena mereka darah pendekar
menyulut saat-saat tak tersangkakan
karena dendam yang dalam
karena korban yang telah berjatuhan
musuh mereka kini bukan dari tanah bali
bali sudah lama angkat kaki
musuh dari sebelah kampung sendiri
karena darah telah jatuh ke tanah
maka congah diteriakkan tak memilah benar salah
Pagutan, 2015
Bait pertama puisi tersebut bercerita tentang sejarah Pagutan, Kota Mataram. Menurut Zakaria (1998) penduduk awal Pagutan adalah imigran petani dari Karangasem, Bali. Mereka datang pada akhir abad ke-16 tepatnya tahun 1593 Masehi dengan tujuan: pertama, mencari daerah baru yang lebih subur; kedua, menghindari gangguan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Awalnya mereka mendirikan pemukiman-pemukiman di Sengkongoq (di kaki Gunung Pengsong), Pagutan, Pagesangan, Mataram, dan Tanaq Embet (di Senggigi). Melihat situasi ini, kerajaan Selaparang sebagai penguasa saat itu di Pulau Lombok—bersama Kerajaan Pejanggik—mengirim prajurit-prajurit di bawah pimpinan Deneq Wirabangsa dan mendirikan pemukiman dengan nama Pedukuhan Sukamulia. Tugas utama Deneq Wirabangsa adalah mengendalikan arus imigran Karangasem. Perkembangan selanjutnya berdirilah Kerajaan Pagutan pada tahun 1622 Masehi dengan raja pertama bergelar Anak Agung Anglurah Karangasem. Menurut versi Babad raja-raja Pagutan, Kerajaan Pagutan berdiri memalui jalan damai. Tetapi menurut analisis Zakaria (1998: 62) berdirinya Kerajaan Pagutan adalah melalui peperangan.
Bait kedua, ketiga, dan keempat, penyair mencari jejak-jejak keturunan para prajurit Kerajaan Selaparang. Mereka telah melepas gelar kebangsawanan karena telah mengerti bahwa yang paling mula di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikianlah yang diajarkan oleh para Tuan Guru. Akan tetapi, seiring jalannya waktu sering terjadi riak-riak antar keturunan prajurit selaparang ini sehingga mereka berselisih antar mereka sendiri.
Puisi adalah filsafat, sedangkan roman, cerita pendek, atau drama adalah ilmu jiwa (Darma, 2020: 88). Puisi-puisi Imam Safwan mengajari kita filsafat hidup masyarakat Lombok Utara dalam puisi-puisi yang bertema tradisi.
Mengutip pendapat Sulistyo (dalam Safwan, 2014: vii) puisi-puisi Imam Safwan secara bentuk dan teknik bisa dibilang sederhana. Dia bukan bagian dari penyair yang gemar berumit-rumit. Bentuk dan pemaknaan puisinya bisa ditangkap dengan segera sehingga mengesankan kepolosan.
Puisi yang unggul bukan hanya puisi yang minta dibaca ulang terus-menerus, tetapi juga mengubah cara kita membaca dan menulis (Dewanto dalam Anwar, 2016: xiv). Apakah puisi-puisi Imam Safwan (2019) memenuhi kriteria di atas? Menurut penulis, Imam Safwan perlu bekerja keras untuk mewujudkannya.***)
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Chairil. 2016. Aku Ini Binatang Jalang: Kumpulan Puisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Darma, Budi. 2020. Solilokui: Kumpulan Esai Sastra. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Safwan, Imam. 2019. Kembali Melaut: Kumpuan Puisi. Yogyakarta: CV Halaman Indonesia.
Safwan, Imam. 2014. Langit Seperti Cangkang Telur Bebek: Ruang-Ruang Puisi Imam Safwan. Mataram: Akar Pohon.
van der Kraan, Alfons. 2009. Lombok: Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940 (Terjemahan dari: Lombok: Conquest, Colonized, And Underdevelopment 1870-1940. Alihbahasa: M. Donny Supanra). Mataram: Lengge.
Widarmanto, Tjahjono. 2018. Yuk, Nulis Puisi: Panduan Mudah dan Sederhana Bagi Pelajar dan Umum. Jakarta: Laksana.
Zakaria, Fath. 1998. Mozaik Budaya Orang Mataram. Mataram: Yayasan “Sumurmas Al Hamidy”.
TENTANG PENULIS
Mazhar, lahir di Gondang, 9 Maret 1976. Lulus di SDN 1 Gondang tahun 1988, SMPN 1 Gangga tahun 1991, dan SMAN 1 Tanjung tahun 1994. Melanjutkan ke Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Mataram (Unram), lulus 1997. Mengambil program S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Muhammadiyah Mataram lulus 2004. Selanjutnya, ia mengambil program S-2 Pendidikan IPS di Universitas Kanjuruhan Malang lulus 2010 dan S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Mataram lulus 2013.
Tahun 1998 lulus sebagai CPNS, ditempatkan di SDN Aik Mual Sekotong Timur Kecamatan Lembar Lombok Barat sampai tahun 2005. Selanjutnya, mengabdikan ilmunya di SDN 4 Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sampai tahun 2012. Promosi sebagai Kepala Sekolah di SDN 3 Gondang tahun 2012 sampai tahun 2016. Dimutasi ke SDN 2 Sambik Bangkol dan SMPN Satap 4 Gangga sampai tahun 2017, menjadi kepala SDN 3 Genggelang Kecamatan Gangga sampai dengan Maret 2019. Promosi sebagai Kasi Kurikulum dan Penilaian PPAUD PNF di Dinas Dikpora KLU sampai dengan Agustus 2021. Sebagai guru di SD Negeri 3 Gondang sejak September 2021 sampai Desember 2022. Januari 2023 sampai saat ini menjadi Kepala SD Negeri 4 Sambik Bangkol.
Karya tulis berupa artikel banyak dimuat di harian Lombok Post. Karya berupa buku telah dihasilkan sebanyak dua judul: (1) Indahnya Kebersamaan: untuk SD/MI Kelas 4, dan (2) Tidak Ada Siswa Bodoh. Karya berupa cerpen pernah terbit di Majalah Titana. Pembicara juga sering berpartisipasi sebagai pemakalah dalam seminar nasional maupun internasional diantaranya: Seminar Internasional Bahasa dan Sastra, Seminar Nasional Bahasa dan Sastra dalam Era teknologi, dan Seminar Nasional Bahasa Ibu VI dalam Rangka Memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Untuk menghubungi Penulis dapat melalui posel: mzhrhar@gmail.com facebook: Mazhar Har Youtube: Mazhar Har dan Terjemahan Alquran Setiap Hari.